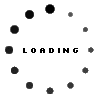Chapter Lima: Perjalanan ke Ruang OSIS
Setelah aku selesai berbicara dengan Makiri-sensei, aku langsung menuju ke atap sehingga aku bisa makan siang bersama Touka. Kemudian aku harus menahan penatnya kelas sore sebelum istirahat sore kami akhirnya tiba.
“Aku melihatmu mengikuti Makiri-sensei ke ruang guru tadi. Apakah ada masalah?” Asakura tiba-tiba muncul di sampingku dan bertanya dengan nada khawatir.
“Oh, uhh, ya. Itu bukan sesuatu yang serius. Jangan dipikirkan,” jawabku.
Dia mungkin mengkhawatirkanku karena semua orang di sekolah merasa kalau Makiri adalah guru yang paling galak di sekolah. Aku yakin dia mengira bahwa Makiri-sensei memanggilku untuk memberikanku khotbah abad ini atau semacamnya.
“Huh. Okelah kalau kamu bilang begitu, bung,” jawab Asakura, tampak yakin dengan penjelasan singkatku. “Omong-omong, dia cukup seksi, tapi dia mengeluarkan, yah, semacam aura menyeramkan setiap kali dia ada di dekat kita. Itu membuatku ingin menjauh darinya, kamu tahu maksudku, kan?”
“Ya, aku paham kenapa kamu berpikiran seperti itu. Meskipun menurutku dia baik, sih.”
“Aku tidak akan pernah mengerti kenapa dia tidak membuatmu takut sama sekali. Itu tidak masuk akal bagiku. Dia selalu terdengar begitu… dingin, kamu mengerti maksudku, kan? Wajah datarnya juga. Rasanya seperti aku tidak akan pernah bisa tahu apa yang sedang dia pikirkan. Memikirkannya saja sudah membuatku merinding.”
“Apakah dia benar-benar semenakutkan itu?” tanyaku tidak percaya. Tiba-tiba, aku teringat dia mengomeli beberapa siswa dari kelas lain baru beberapa hari yang lalu. Mereka tampak hampir terkencing di celana.
“Kamu seharusnya mendengar hal-hal yang dia katakan ketika dia memanggilku tempo hari. Ah, kenangan itu…” kenang Asakura, menutup matanya dan kemudian mamasang wajah suram. Ini pasti percakapan yang Makiri-sensei katakan sebelumnya.
Aku menunggu dia melanjutkan dalam diam.
“Tapi kamu benar-benar membelanya,” tambahnya tiba-tiba. “Apakah kamu menyukainya atau semacamnya? Apakah kamu menyukai wanita yang memberimu tatapan mematikan?”
“Tidak, bukan seperti itu.”
Asakura pun menggosok hidungnya dengan ringan sebagai tanggapan dan menyeringai. “Aku… Aku sebenarnya tidak keberatan untuk bersamanya.”
“Oh, benarkah?”
Yah, ini tidak terduga. Daripada mengkhawatirkanku, kurasa dia sebenarnya cemburu? Mungkinkah dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Makiri-sensei? Aku tidak benar-benar ingin dia jadi salah paham, jadi aku tetap diam.
“Bayangkan saja, Bung—dia mungkin tipe orang yang awalnya bersikap dingin, tapi ada momen langka di mana dia memberkatimu dengan senyum yang tak terlupakan. Ah, sempurna.”
“Ya, itu cukup indah ketika dia melakukan itu,” aku membenarkan.
Asakura tidak salah, tapi menurutku dia sedikit melebih-lebihkan. Senyum Makiri-sensei memang indah, tapi menurutku itu tidak semenakjubkan yang Asakura katakan. Karena aku sedang tidak mood untuk berdebat dengannya atau semacamnya, aku akan mengiyakannya saja.
“Apa yang kalian bicarakan? Apanya yang ‘indah’?” Kana tiba-tiba angkat bicara. Mejanya tepat di sebelah meja kami, jadi mudah baginya untuk memulai percakapan.
“Oh, kami sedang membicarakan Makiri-sensei. Dia memanggil Tomoki beberapa waktu lalu,” jawab Asakura.
“Benarkah? Apakah kamu baik-baik saja?” tanyanya padaku, jelas khawatir. “Yang kutahu tentangnya adalah dia cukup galak.”
“Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir,” jawabku dengan melambaikan tangan.
“Senang mendengarnya, tapi aku penasaran—apa yang kamu katakan tentang senyumnya barusan?” dia melanjutkan.
Dia memberiku senyum yang cerah dan ceria, tapi mengingat kalau dia adalah Kana, dia sama sekali tidak bahagia sekarang. Segalanya bisa menjadi buruk dengan sangat cepat tergantung pada jawabanku. Asakura, wahai temanku, nasibku ada di tanganmu. Aku segera melirik Asakura, berharap dia mengerti isyaratku, dan dia balas tersenyum padaku. Senang mengetahui dia membantuku.
“Oh, itu,” dia menjelaskan dengan cepat. “Kami barusan berbicara soal bagaimana bahkan seseorang yang sedingin Makiri-sensei pun mungkin memiliki saat-saat di mana dia tersenyum. Aku dan Tomoki setuju bahwa itu akan sangat menakjubkan untuk dilihat.”
Sialan, Asakura. Cara yang bagus untuk menambahkan bensin ke dalam api.
“Oooh, jadi itu yang kamu suka, Yuuji-kun? Menarik…” katanya dengan tatapan tajam.
“Uhh, yah, dia mungkin sedikit melebih-lebihkan,” kataku dengan gelisah.
“Aku merasa lucu bagaimana kamu selalu memanggilku ‘imut’ dan ‘salah satu gadis tercantik di sekolah,’ tapi kamu jugs memikirkan hal yang sama pada Makiri-sensei. Belum lagi hubunganmu dengan Touka-chan. Kamu tentunya ingin menjaga agar pilihanmu tetap terbuka, ya?” bisiknya.
Oke, akan gawat jika kami berdua tidak melakukan sesuatu di sini. Aku meletakkan tanganku di bahu Asakura—mungkin kali ini, sikap diamku akan bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan.
“Huh. Kupikir dia akan menghajarmu habis-habisan karena itu, tapi entah kenapa, aku merasa seperti kamu lolos dengan mudahnya,” ujar Asakura.
Tunggu, benarkah?
“Jika kamu bilang begitu…”
Dia terlihat sangat menyedihkan sekarang sehingga aku tidak sanggup untuk tidak setuju.
☆
Kelas akhirnya berakhir. Saat aku akan mengemasi barang-barangku dan pulang, Ike memanggilku.
“Hei, Yuuji, bisakah kamu datang ke ruang OSIS sebentar? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu.”
Dia mungkin ingin aku membantunya dengan beberapa hal. Aku akan ikut, karena bukan seperti aku punya rencana lain juga sih. Selama aku memberi tahu Touka terlebih dahulu, dia biasanya tidak masalah dengan itu.
“Tentu, Bung.”
“Bagus. Ikuti aku,” katanya sambil tersenyum dan dengan cepat meninggalkan kelas.
Saat aku menuju ke ruang OSIS, aku mengirimkan pesan singkat ke Touka yang menjelaskan bahwa aku akan melakukan beberapa hal di sana.
“Ok Senpai, sampai ktm dsn,” jawabnya.
“Kurasa Touka akan bergabung dengan kita,” kataku pada Ike saat kami berjalan menuju ruangan.
Dia menjawab dengan tertawa. Apakah aku mengatakan sesuatu yang lucu?
“Oh, jangan salah paham,” tambahnya. “Itu hanya membuatku berpikir tentang betapa akrabnya kalian berdua.”
Aku merasa sangat malu. Maksudku, dia temanku. Aku tahu kalau aku harus lebih terbuka dengannya mengenai hal-hal ini sekarang. Sangat menyenangkan bahwa dia mengenalku dengan cukup baik hingga dia hampir selalu dapat mengetahui apa yang aku pikirkan.
“Kurasa begitu,” jawabku, tidak tahu harus bagaimana lagi.
Setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Ketika kami masuk, kami menyadari bahwa Tanaka-senpai, salah satu sekretaris, dan Suzuki, bendahara OSIS, sudah menunggu kami di sana.
“Hei, teman-teman. Bagaimana kabar kalian?” tanya Ike.
“Yo,” mereka berdua menjawab bersamaan.
Keduanya tidak memperlakukanku seperti sebuah penampakan menyeramkan—tidak seperti siswa lainnya di sekolah—jadi aku merasa nyaman dengan mereka.
“Yo,” sapaku ke mereka.
“Kalian berdua datang cukup awal. Kudengar Tatsumiya akan terlambat hari ini, tapi bagaimana dengan Taketori-senpai? Dimana dia?” tanya Ike.
“Dia mungkin tidak ingin berkumpul hari ini.”
“Yeeeah… Kurasa dia tidak akan datang,” kata Ike sambil menghela nafas.
Aku kenal hampir semua orang di OSIS, tapi sayangnya Tatsumiya adalah pengecualian karena aku tidak bisa mengingat wajahnya dengan benar. Selain itu, pria Taketori ini adalah satu-satunya orang yang belum pernah aku temui.
“Oh, begitukah. Oke, begitu Touka tiba, aku akan menjelaskan kenapa aku memanggil kalian hari i—” Ike mengawali, tapi segera terganggu oleh suara ketukan pintu.
“Ayo masuk!” seru Suzuki.
“Hei, teman-teman! Apakah Sayangku ada di sini? Yuuji-senpaaaai!” sembur Touka saat dia menerobos masuk.
“Yep, Sayangmu di sini baik-baik saja,” kata Ike sambil berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa.
Saat Touka melihatku, dia bergegas dan menempelkan dirinya di sampingku. “Sepertinya kakakku berhasil menjeratmu lagi, ya, Senpai? Dia sangat jahat! Beraninya dia mencuri waktu romantis kita yang berharga, kan?! Tapi tidak apa-apa, Senpai! Aku sudah di sini sekarang, dan itulah yang terpenting! Sini, aku akan memelukmu erat-erat sehingga kamu tidak bersedih lagi!”

Apa yang dia bicarakan sih? Kenapa dia merentangkan tangannya?
“Astaga, Senpai. Jangan menatapku seperti itu! Kamu akan membuatku tersipu malu!” dia nyaris menjerit.
“Haaah. Ngomong-ngomong, untuk apa kita di sini tadi?” Aku bertanya pada Ike, menghapus 10 detik terakhir dari ingatanku. Touka sedikit cemberut saat aku mengabaikannya, tapi dia dengan cepat kembali normal.
“Oke, jadi coba lihat ini,” kata Ike sambil menyerahkan setumpuk kertas yang dijepit menjadi satu. “Biasanya, setiap awal Agustus, para anggota OSIS akan mengadakan perjalanan singkat ke suatu tempat. Aslinya, tujuan perjalanan itu akan menjadi kesempatan yang bagus bagi para anggota untuk mengenal satu sama lain lebih baik, mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, dan bertukar pikiran soal bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, tapi, sebenarnya, itu hanyalah alasan bagi semua orang untuk mendapatkan sedikit hari libur.”
“Huh. Aku tidak tahu ada yang sepert itu,” jawabku.
“Ya, ada,” jawab Suzuki dengan anggukan.
“Aku ingin kamu bergabung dengan kami, Yuuji. Kamu memang harus menutupi sebagian biayamu sendiri, tapi itu tidak akan terlalu banyak. Bagaimana menurutmu?” tanya Ike.
Aku melirik kertas-kertas yang dia berikan padaku, yang berisi total biaya berdasarkan biaya per orang selama perjalanan tahun lalu. Ya, itu benar-benar tidak banyak, meskipun uang bukanlah masalahku.
“Dan kalian tak masalah kalau aku ikut, meskipun aku bukan bagian dari OSIS?”
Ike mengangguk. “Mhm. Aku sudah bertanya pada guru pengawas kami, dan dia berkata kamu bisa ikut selama kamu tidak keberatan. Hal yang sama berlaku juga untuk Touka.”
“Huh? Kenapa aku?” seru Touka, jelas terkejut.
“Kamu dan Yuuji telah banyak membantu kami. Dia telah membantu sejak tahun lalu, dan kamu mulai ikut membantu sejak pertemuan studi sekolah pertama, ingatkan? Secara teknis, perjalanan ini dimaksudkan untuk membahas pengembangan sekolah, jadi orang-orang di luar OSIS dapat bergabung—terutama jika mereka telah berkolaborasi dengan kami dan ingin melihat sekolah berkembang. Kami juga membuat pengecualian tahun lalu. Aku tidak merasa kalau kalian tidak bisa menjadi bagian dari itu jika kalian benar-benar mau.”
Oh, itu terjadi tahun lalu juga? Aku mengerti sekarang.
“Yah, aku tidak memaksa,” dia meyakinkan kami. “Luangkanlah waktu beberapa hari ini untuk mempertimbangkannya sebelum memberikan jawabanmu.”
“Senpai, kita harus ikut perjalanan ini!” seru Touka begitu Ike selesai berbicara.
“Kamu benar-benar tampak bersemangat tentang semua ini,” kataku.
“Ayolah! Kedengarannya menyenangkan, kan? Apakah kamu tidak mau?”
“Kurasa kamu benar,” aku mengakui setelah jeda untuk memikirkannya. “Kedengarannya memang menarik. Jadi ya, kami akan ikut jika kalian tidak keberatan.”
Ike menghela nafas lega. Apakah dia benar-benar berpikir kalau aku akan menolak tawarannya atau semacamnya? “Bagus! Senang mendengarnya. Aku akan memberikan rinciannya dalam beberapa hari. Apakah kamu tak keberatan menunggu sampai saat itu?”
“Kita akan bersenang-senang, aku yakin itu,” kata Tanaka-senpai.
“Ya! Jujur saja, aku tidak sabar menunggu perjalanan ini,” lanjut Suzuki.
“Oh, benar—aku hampir lupa. Kami perlu dokumen ini ditandatangani oleh orang tuamu, hanya untuk jaga-jaga. Yah, maksudku, untuk mendapatkan izin mereka dan yang lainnya. Tanda tangan orang tuamu yang mana pun tak masalah, jadi begitulah,” tambah Ike sambil menyerahkan lembaran lain lagi.
Aku ragu sejenak sebelum menjawab, “Ya, tidak masalah.” Mendengarnya mengatakan itu mengingatkanku pada wajah ayahku.
Ike menatapku sejenak, lalu meletakkan tangannya di bahuku dan melanjutkan. “Baiklah kalau begitu. Aku akan menyerahkannya kepada Makiri-sensei sehari sebelum perjalanan, jadi kamu punya waktu sampai saat itu… tapi lebih cepat, lebih baik.”
“Uhh, Senpai?” tanya Touka, menatapku.
Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku memaksakan senyum, berpamitan, dan meninggalkan ruangan.
Touka menyusul tak lama kemudian. Kami meninggalkan halaman sekolah dan menuju stasiun kereta. Ada jeda keheningan yang lama di antara kami sebelum Touka akhirnya memecahkan keheningan.
“Senpai, apakah kamu tidak akur dengan orang tuamu?” tanya Touka, langsung ke intinya.
Aku mencoba berpura-pura tidak sadar, berpura-pura tidak mendengar pertanyaannya, tapi aku akhirnya menyerah di bawah tatapannya yang gigih. “Orang tuaku bercerai beberapa waktu lalu, dan aku tinggal bersama ayahku sekarang. Meskipun kami sekarang belum berbicara selama berbulan-bulan.”
“Oh… Begitu ya. Seharusnya aku tidak menanyakan itu. Maaf, karena telah tidak sopan,” jawabnya sambil melihat ke bawah.
Sial. Aku tidak bermaksud membuatnya merasa tidak enak. Kurasa aku bisa memberitahunya lebih banyak tentang itu.
“Itu bukan seperti aku kecewa dengan perceraian mereka atau semacamnya. Adapun ayahku… Yah, anak remaja selalu bertengkar dengan orang tua mereka, kan? Kurasa aku sama seperti yang lain.”
“Kenapa kalian tidak akur? Apakah terjadi sesuatu?” tanyanya. Mungkin fakta bahwa aku mau terbuka padanya membuatnya merasa sedikit lebih berani.
“Ayahku dulu seorang polisi. Dia selalu menanamkan gagasan ke dalam diriku bahwa aku harus bertarung sendiri dalam menghadapi masalahku jika aku ingin memperbaiki kesalahan dalam hidupku. Anggap saja itu tidak berakhir dengan baik. Kurasa aku menafsirkan kata-katanya terlalu harfiah—dulu, aku adalah tipe pria yang akan menghajar orang untuk menyelesaikan semua masalahku.”
Touka tidak mengatakan apa-apa, malahan dia tetap menjaga kepalanya menghadap ke bawah sambil mendengarkan dengan seksama.
“Aku tidak pernah benar-benar memberitahumu tentang apa yang terjadi tahun lalu, kan? Maksudku, alasan aku mendapatkan reputasiku di sekolah.”
“Ya, kamu belum memberitahuku.”
“Ceritanya membosankan, tapi begini,” kataku. Lagian, dia perlu mengetahuinya suatu saat.
Ini mengingatkanku…
☆
Aku sedang dalam perjalanan pulang hari itu, dengan kesal berjalan susah payah melewati genangan air besar. Saat itu adalah pertengahan musim hujan, yang berarti berhari-hari diguyur hujan tanpa henti. Aku membencinya—cuaca buruk selalu merusak suasana hatiku. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya seperti itu—aku tidak marah pada alam; Aku kesal pada hampir semua orang di sekolahku. Guru, siswa… tidak peduli siapa itu. Mereka selalu kabur begitu melihatku. Dan setiap kali aku melewati mereka, aku bisa mendengar mereka bergosip pelan tentangku.
Tiga bulan telah berlalu sejak aku mulai masuk SMA, dan tidak ada yang berubah—semua orang masih menghindariku seperti aku ini wabah.
Aku tidak pernah bermaksud untuk tampil sebagai pria yang menakutkan, tapi kurasa kombinasi dari tidak bersikap sangat baik, ditambah lagi tidak sering berbicara dengan orang lain, sudah cukup untuk membuatku menakutkan.
Satu-satunya yang punya nyali untuk berbicara denganku saat itu adalah Ike. Dia sama sekali tidak takut padaku. Aku akui, saat itu, aku tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia. Aku pernah melihat orang seperti dia sebelumnya—pria yang mencoba berteman dengan semua orang, tapi selalu memiliki motif tersembunyi. Aku memastikan untuk tetap menghargainya pada saat itu sambil terus menjaga kewaspadaanku di dekatnya. Dalam pikiranku, aku yakin dia tidak tulus padaku.
Tahun pertama SMA-ku cukup lancar, itu jika kalian tidak menghitung perceraian orang tuaku. Sejujurnya, aku sudah tahu kalau itu semua hanyalah masalah waktu. Ibuku takut pada ayahku, tapi dia bertahan sampai aku masuk SMA sehingga perpisahan itu tidak mengacaukan ujian masukku.
Dan untuk ayahku, pria itu pada dasarnya menikah dengan pekerjaannya. Aku bersumpah, dia menyukai pekerjaannya lebih dari kami. Dia hampir tidak pernah pulang dan tidak pernah peduli pada kami.
Tetap saja, aku cukup kesal ketika aku mengetahui tentang perceraian itu melalui surat yang dikirim ibuku setelah dia lari pulang ke rumah orang tuanya. Ayahku juga meninggalkanku kertas catatan di rumah, hanya menyatakan bahwa dia dan ibuku sudah tidak lagi menikah.
Pagi itu aku sedang kesal dengan seluruh situasi itu ketika aku melewati skenario yang tidak asing: sekelompok preman rendahan sedang mengelilingi beberapa siswa dari sekolah bergengsi lain terdekat.
“Hei, bukankah sudah kubilang pada kalian orang-orang bodoh untuk membawakan kami uang?” bentak salah satu dari mereka.
“Bang, kami tidak punya uang. Beri kami keringanan,” pinta salah satu siswa.
Seperti yang kubilang, ini bukanlah pertama kalinya aku melihat orang-orang ini bersama. Meskipun daerah itu cukup ramai, tidak ada satu pun pejalan kaki yang mau membantu—kebanyakan hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Segala sesuatu tentang itu membuatku kesal: siswa SMA yang menolak untuk membela diri mereka sendiri, para bajingan yang memangsa yang lemah, orang-orang yang menutup mata terhadap semuanya. Tapi yang paling membuatku kesal, aku kesal pada diriku sendiri karena marah atas omong kosong bodoh itu.
Jadi apa yang aku lakukan?
☆
Ya… Aku berkelahi dengan preman untuk membantu para siswa itu melarikan diri.
“Apa masalahmu, yo?!”
Para bajingan itu mencoba memanggil teman-teman mereka untuk meminta bantuan, tapi pada akhirnya aku masih berhasil menghajar mereka semua.
Sayangnya, itu tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Bukan hanya memperburuk suasana hatiku yang sudah buruk, tapi reputasiku di sekolah semakin tercoreng. Beberapa siswa telah menyaksikannya, yang berarti semua orang di sekolah juga segera mengetahuinya. Orang tuaku dipanggil, istilah “dikeluarkan” dilontarkan, dan aku ditempatkan di bawah tahanan rumah selama beberapa hari.
Untungnya, hal-hal tidak meningkat sampai ke titik dikeluarkan, tapi segalanya jelas meningkat saat ke rumah. Setiap kali aku berkelahi—terlepas dari penyebab atau konteksnya—ayahku akan memukuliku habis-habisan. Perkelahian ini pun tidak terkecuali.
“Beraninya kau? Berani-beraninya kau, j*ncuk?! Yang kau lakukan hanyalah mempermalukan dirimu sendiri dan keluarga ini,” teriaknya, mencengkeram kerah bajuku dan menampar wajahku. “Sudah kubilang berulang-ulang—jangan terlibat dalam perkelahian! Kau hanya perlu menggunakan kekerasan jika tidak ada alternatif lain atau kau perlu melindungi diri sendiri! Apa kau tuli? Apa perlu aku memberimu pelajaran?!”
Biasanya, aku akan menerima pukulannya dalam diam karena dia cenderung benar, tapi hari itu, segalanya berbeda.
“Apakah menurutmu memukuliku sekarang adalah tindakan yang sangat benar? Hah?” tanyaku.
“Iya. Jika wortel tidak bekerja, maka tongkat pasti akan bekerja,” jawabnya.
“Tidak heran Ibu kabur—dia pasti sudah muak dengan sikapmu yang sok suci itu. Kau selalu mencoba membenarkan perbuatan apa pun yang kau ingin lakukan.”
“Apa kau bilang?” geramnya. Itu adalah ekspresi paling marah yang pernah aku lihat padanya.
“Kubilang, ‘tidak heran Ibu kabur.’ Kau selalu memperlakukan kami seperti sampah dengan kedok menjadi ayah yang baik, tapi kenyataannya, kau tidak pernah melakukan apa-apa.”
“Baiklah, itu sudah cukup. Tutup mulut sampahmu itu.”
Dia akan mendorongku ke samping, tapi segera berubah pikiran dan melemparkan pukulan ke arahku. Aku berhasil merunduk tepat waktu dan dengan cepat meraih lengannya untuk menahannya.
“Aku terlibat dalam perkelahian itu karena aku melindungi sekelompok anak-anak dari sekelompok bajingan yang mencoba merampas uang mereka. Bukankah itu merupakan keputusan yang tepat? Ataukah mungkin aku seharusnya mengabaikan mereka seperti yang lain dan berpura-pura itu tidak terjadi? Atau apa? Haruskah aku membiarkan orang-orang itu menghajarku?” ocehku sekaligus. Suara rasional di balik kepalaku berteriak bahwa aku seharusnya tidak repot-repot terlibat dalam perkelahian itu, tapi aku masih ingin mendengar apa yang akan ayahku katakan tentang semuanya.
Dia tidak menjawab, yang membuat itu hanya memicu kemarahanku lebih jauh.
“Katakanlah sesuatu, dasar bajingan!” teriakku.
Dan tiba-tiba, tanpa aku sadari, keadaan telah berubah sepenuhnya. Alih-alih ayahku memukuliku, akulah yang memukulnya tanpa batas. Mengingat dia adalah mantan perwira, aku tahu kalau dia bisa menerimanya. Aku hanya terus meratap padanya tanpa ampun, satu pukulan demi pukulan. Setelah beberapa saat, aku berhenti; dia terkapar, tidak bergerak, di lantai. Sekarang akulah yang di atas, memandang rendah dia.
“Ada apa, pak tua? Apakah kau tidak bangga padaku? Aku membela diri, seperti yang kau ajarkan padaku selama bertahun-tahun ini.”
Aku mengangkat kerahnya dan membawanya mendekat, seperti yang dia lakukan padaku beberapa saat lalu. Saat itulah aku menyadari bahwa ekspresi marah ayahku telah menghilang. Dia hampir menangis, gemetar dan ketakutan. Takut padaku. Dia bukan lagi ayah yang menjunjung tinggi gagasan keadilannya dengan kekerasan, tapi seorang pria lemah yang takut pada putranya sendiri karena dia tidak bisa lagi mengendalikannya.
Aku mengendurkan cengkeramanku dan membiarkannya merosot ke lantai, di mana dia terbaring kesakitan dan gemetar ketakutan.
Sudah terlambat; apa yang terjadi, terjadilah. Dan sejak hari itu, kami tidak pernah berbicara lagi.
☆
Itu semua berkat Ike dan Makiri-sensei sehingga aku tidak dikeluarkan. Ike entah bagaimana berhasil melacak orang-orang yang aku selamatkan, dan mereka menghubungi sekolah untuk melindungiku. Dia bahkan menemukan para bajingan itu dan entah bagaimana meyakinkan mereka untuk diam dan tidak pernah menginjakkan kaki di daerah itu lagi. Serius, dia melakukan banyak upaya untuk pria yang jarang berbicara dengannya.
Makiri-sensei, di sisi lain, percaya ceritaku dari awal, tidak seperti yang lain. Meskipun guru baru di sekolah, dan dia bahkan bukan guru di kelasku, Ike mengatakan padaku bahwa dia telah berjuang mati-matian untuk meyakinkan semua orang bahwa aku tidak bersalah.
Dengan bantuan mereka, itulah akhirnya.
☆
Aku menyelesaikan ceritaku dan melihat ke arah Touka, yang menatap ke bawah dengan kaget. Padahal kukira dia akan membuat suatu komentar sinis tentang ceritaku yang membosankan.
Tiba-tiba, dia meraih tanganku dan tersenyum tulus. “Terima kasih telah mempercayaiku dengan ini, Senpai. Kamu pasti telah mengalami masa sulit. Kuharap aku ada di sana bersamamu saat itu terjadi. Sekarang aku mengerti kenapa kamu tidak berhubungan baik dengan ayahmu.”
“Yah…” gumamku sambil membuang muka.
“Hm? Apa? Ada yang salah?”
“Bukannya aku membenci pak tua itu atau semacamnya. Sekarang setelah aku mengingatnya kembali, aku sadar bahwa keadaanku di sekolah dan di rumah mendorongku untuk melakukan itu. Pada akhirnya, akulah yang sudah gatal untuk berkelahi, meski pun aku menutupinya dengan alasan untuk menyelamatkan orang-orang itu.”
“Itu tidak benar sama sekali!” teriaknya. “Kamu mungkin buaya darat diskonan yang buruk dalam berteman, tapi kamu bukanlah preman! Tentu, kamu akan menggunakan kekerasan jika diperlukan, tapi kamu tidak akan pernah berkelahi hanya untuk kesenangan! Kamu adalah pria yang baik, dan aku tahu itu secara langsung!”
“Apakah ini usahamu untuk menghiburku?”
Sejujurnya, itu melegakan karena dia masih mempercayaiku setelah aku menceritakan semua ini padanya. Aku benar-benar merasa bahagia dari lubuk hatiku.
“Apakah kamu benar-benar merasa bersalah pada ayahmu sekarang?” tanyanya.
Aku mengangguk. “Ya, aku—yah, masih merasa—sangat sebal pada diri sendiri… dalam lebih dari satu cara. Aku sudah berpikir untuk meminta maaf padanya beberapa kali sebelumnya, tapi pada akhirnya aku selalu mundur.”
“Maka seluruh persoalan tanda tangan untuk perjalanan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna!” serunya sambil tersenyum. “Tidakkah menurutmu dia akan senang karena kamu punya teman untuk pergi berlibur? Maksudku, itu menunjukkan bahwa kamu tidak akan berkelahi lagi.”
Aku berhenti sejenak untuk berpikir. “Semoga itu yang terjadi.”
“Kamu selalu bisa mengatakan padanya bahwa kamu mendapatkan pacar yang kebetulan, seperti, sosok istri ideal. Dalam hal ini, aku akan mengizinkanmu mengatakan itu.”
“Siapa yang kamu bicarakan?”
“Tidak perlu malu, Senpai. Kadang-kadang kamu perlu mengakuinya,” katanya dengan nada bangga dan menggelengkan kepalanya.
“Sepertinya kita sudah sampai di stasiun,” kataku.
“Ya ampun. Mencoba kabur sekarang ya, dasar pemalu?”
“Maaf, Tuan Putri Peech, tapi bagaimanapun juga aku harus pulang.”
TLN: Tuan Putri Peech adalah karakter dalam game Mario Bros.
“Tunggu, apa? ‘Peech’? Aku sedang berbicara tentangmu yang jadi super-duper pemalu, Senpai. Apa yang sedang kamu bicarakan, sih?” tanya Touka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia terkikik, mencondongkan tubuh, dan berbisik di telingaku, “Apa pun yang terjadi, aku harus bilang bahwa aku sangat menantikan untuk menghabiskan malam pertama kita bersama, Senpai.”
Napasnya menggelitikku sedikit. Sensasinya, dikombinasikan dengan mata anak anjingnya, membuatku bergetar. Dia menyeringai nakal sebagai tanggapan.
“No comment,” jawabku.
Jawabanku hanya membuatnya semakin berani. Sampai kami berpisah jalan, dia tidak pernah menghapus seringai nakal dari wajahnya.
☆
Aku tiba di rumah tak lama setelah itu dan melihat sepatu ayahku sudah terjajar di pintu masuk. Kurasa dia pulang lebih awal dariku hari ini. Aku mengintip ke ruang tamu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia mungkin sudah ada di kamarnya.
Aku menuju ke kamarnya, membuka tasku, mengeluarkan formulir, dan membuka pintu. Benar saja, dia ada di sana. Dia sedang mendengarkan musik dengan headphone dan membaca buku, jadi masuk akal dia tidak mendengarku masuk. Saat aku menatapnya, aku tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak lebih pendek daripada yang aku ingat.
Pada akhirnya, aku tidak sanggup untuk mengatakan apa pun padanya. Sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya sekarang—jika aku punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan dengannya, itu pasti sudah lama sekali terjadi. Aku menutup pintu dan menuju ke kamarku.
Maaf, Touka, tapi aku tidak sekuat yang kamu kira. Aku tahu kalau kamu mencoba menyemangatiku untuk memperbaiki hubunganku dengannya, tapi aku hanya tidak bisa.

![Yuujin-chara no Ore ga Motemakuru Wakenaidarou? Bahasa Indonesia [LN] Yuujin-chara no Ore ga Motemakuru Wakenaidarou? Bahasa Indonesia [LN]](https://i2.wp.com/fuyu-novel.my.id/wp-content/uploads/2022/10/1-10.jpg?resize=150,150)
![Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu Bahasa Indonesia [WN] Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu Bahasa Indonesia [WN]](https://i1.wp.com/fuyu-novel.my.id/wp-content/uploads/2022/10/1.jpg?resize=151,215)
![Genjitsu de Love Comedy Dekinai to Dare ga Kimeta? Bahasa Indonesia [LN] Genjitsu de Love Comedy Dekinai to Dare ga Kimeta? Bahasa Indonesia [LN]](https://i1.wp.com/fuyu-novel.my.id/wp-content/uploads/2022/10/1.1-1.jpg?resize=151,215)
![Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu Bahasa Indonesia [LN] Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu Bahasa Indonesia [LN]](https://i0.wp.com/fuyu-novel.my.id/wp-content/uploads/2024/01/1-scaled.jpg?resize=151,215)